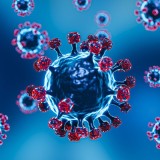TIMES MAJALENGKA, MAJALENGKA – Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menyadarkan kita bahwa Indonesia berada pada wilayah rawan yang menuntut kesiapsiagaan sepanjang tahun.
Ribuan warga mengungsi, ratusan rumah rusak, dan infrastruktur lumpuh di berbagai daerah. Pemerintah, lembaga kemanusiaan, aparat lokal, dan komunitas masyarakat sipil bergerak cepat, mengevakuasi korban hingga menyalurkan bantuan ke daerah-daerah terdampak.
Namun, ada pemandangan menarik yang menggelitik di tengah dinamika penanganan bencana ini: hilangnya kehadiran partai politik dan para relawan politik yang biasanya sangat mudah ditemui pada momentum pemilu. Tidak terlihat atribut, rompi, baliho, atau spanduk yang menandai keterlibatan partai, berbeda dengan suasana menjelang pemilu ketika relawan dan kader seakan berlomba tampil sebagai pahlawan kemanusiaan.
Fenomena berkurangnya kehadiran partai politik dalam situasi bencana bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan, tetapi dapat dipahami melalui berbagai dinamika komunikasi dan manajemen organisasi. Pertama, partai politik tampaknya sangat berhati-hati karena khawatir dianggap memanfaatkan bencana untuk kepentingan pencitraan. Publik saat ini semakin kritis, dan sedikit saja ada simbol partai dalam kegiatan kemanusiaan, framing oportunisme politik dapat dengan cepat muncul, terutama di media sosial.
Karena tahun politik berikutnya masih jauh, yakni Pemilu Tahun 2029, partai agaknya memilih untuk meredam eksposur publik agar tidak memperburuk citra atau memancing komentar negatif. Bantuan mungkin tetap disalurkan, tetapi lebih sering melalui jaringan internal atau organisasi sayap tanpa memperlihatkan identitas politiknya.
Kedua, meski memiliki struktur organisasi yang luas, tidak semua partai politik memiliki kapasitas tanggap darurat. Penanganan bencana membutuhkan kemampuan logistik, koordinasi lintas lembaga, dan keterampilan teknis tertentu yang biasanya dimiliki oleh lembaga kemanusiaan profesional, bukan organisasi berbasis kepentingan elektoral.
Pada masa kampanye, relawan partai bergerak masif karena ada motivasi elektoral, struktur komando yang jelas, serta pendanaan yang mengalir. Tetapi saat bencana datang jauh dari momentum politik, mobilisasi besar-besaran tidak selalu menjadi prioritas, baik secara strategis maupun operasional.
Ketiga, dominasi respons negara dan masyarakat sipil juga menjadi faktor. Pemerintah daerah, kementerian, lembaga penanggulangan bencana, TNI, Polri, dan berbagai organisasi kemanusiaan mengambil posisi terdepan dalam penanganan bencana kali ini.
Ketika negara mengambil alih pusat kendali, ruang tampil bagi partai politik menjadi semakin sempit. Di banyak daerah, aksi cepat komunitas lokal dan relawan non-politik jauh lebih terlihat karena mereka tidak dibebani agenda elektoral ataupun perhitungan reputasi.
Keempat, masyarakat sebenarnya lebih membutuhkan tindakan nyata ketimbang simbol politik. Dalam situasi krisis dan korban jiwa, masyarakat menginginkan kepastian keselamatan, distribusi logistik yang merata, dan akses layanan yang cepat.
Identitas politik bukan hanya tidak relevan, tetapi bisa memancing kritik karena dianggap tidak sensitif terhadap rasa duka dan keprihatinan publik. Di sinilah kita melihat bahwa efektivitas komunikasi politik pada situasi bencana sangat berbeda dari dinamika komunikasi pada masa pemilu. Ketika nyawa menjadi prioritas, simbol politik menjadi tak berarti.
Bencana yang melanda Sumatera menjadi pelajaran penting bagi partai politik. Jika ingin tetap relevan dan dipercaya, partai seharusnya membangun kapasitas kemanusiaan yang nyata dan berkelanjutan, bukan hanya hadir saat kampanye.
Mereka perlu mengembangkan unit tanggap bencana yang profesional, kolaboratif, dan responsif sepanjang tahun sebagai bentuk tanggung jawab moral, bukan sekadar strategi citra. Kepekaan kemanusiaan harus berdiri di atas kalkulasi elektoral, karena legitimasi politik sejatinya dibangun melalui kedekatan dengan rakyat dalam situasi paling sulit.
Solidaritas kemanusiaan tidak boleh menunggu jadwal pemilu. Bencana Sumatera harus menjadi refleksi: apakah partai politik bersedia bergerak menuju paradigma baru di mana kemanusiaan dipandang sebagai bagian dari amanah politik, atau tetap terjebak dalam pola lama yang hanya aktif ketika elektabilitas dipertaruhkan.
Demokrasi yang sehat tidak diukur dari meriahnya kampanye, tetapi dari kemampuan semua elemen politik untuk hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan.
***
*) Oleh : Adi Junadi, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Majalengka.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |